RAMON
Pertangahan April itu aku menerima telepon.
“Hallo…!” kataku.
“Hai Emma, ini Kim. Apa ibumu ada dirumah?”
Kim adalah teman ibuku. Mendengar nada suaranya, aku merasa ada yang sangat penting.
“Ia sedang keluar kota, tapi akan kembali malam ini,” jawabku, bertanya-tanya apa yang terjadi.
“Oh, kalau begitu apa ayahmu ada?” jawabnya cepat.
Ayahku sedang mandi, jadi kukatakan bahwa ia tak dapat bicara dengannya sekarang. Lalu Kim berpesan agar ayahku menelponnya segera mungkin. Aku menutup telepon sambil berpikir, apa sih yang sangat penting? Apakah ada yang salah? Apa yang terjadi pada anaknya Baim, yang sekelas denganku waktu kanak-kanak?
Aku duduk sambil melanjutkan membaca, tapi hatiku tak tenang.
Setelah itu, aku sibuk membaca sampai lupa memberitahu menelpon Kim. Padahal ayahku sudah agak lama keluar dari kamar mandi. Langit sudah mulai gelap, dan waktunya makan malam. Aku dikejutkan oleh deringan telepon, dan melompat mengambilnya.
Ternyata Kim lagi. Aku memberikan telepon tersebut ke ayahku yang keluar dari dapur karena mendengar dering telepon. Aku kembali membaca, tetapi tentu saja tidak konsentrasi. Sambil pura-pura membaca, aku menguping mendengarkan pembicaraan mereka.
Suara ayahku terlihat serius dan tegamg, dan semakin lama aku mendengarkan, suaranya semakin terdengar sedih. Aku mendengar kata-kata seperti “Aku turut berduka.” dan “Dia anak yang baik.”
Perutku mendadak terasa aneh. Apa maksudnya, “Dia anak yang baik?” Siapa yang mereka bicarakan? Aku merasa tegang dan takut.
Aku mendengar suara ayahku perlahan mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Lalu terdengar suara langkah ayahku menghampiriku. Aku siap mendengar cerita ayahku. Ayah berdiri di sampingku dan berdiam sejenak. Ia terlihat tegang.
“Emma,” ia mulai berbicara. Aku menatapnya menebak-nebak apa kabar yang akan disampaikan.
“Ramon meninggal,” katanya dengan cepat.
Perutku terasa melonjak. Aku terkejut. Apa pendengaranku salah? Ini tidak mungkin, tapi ayahku mungkin bergurau tentang hal seperti ini.
Ramon telah menjadi teman sekelasku sejak kelas 1. Ia telah mengambil bagian pemting di sekolahku. Ia datang dari Jerman tanpa dapat berbahasa Indonesia sedikitpun. Tapi ia belajar dengan cepat karena kegemarannya membaca. Ia senang berpetualang di alam bebas, hebat dalam bermain sepak bola dan anak yang baik. Ia menjadi teman sekelas dan satu timku. Sebenarnya aku pernah suka padanya. Tapi sekarang ia telah tiada.
Aku teringat kejadian di sekolah saat ia dan Joshua bermain kasar. Ramon memukul kepalanya, tapi ia tampak tak peduli, meski Jo sedang tak enak hati.
“Tadi di sekolah ia memukul kepala Jo keras sekali, sepertinya bercanda,” aku menceritakan pada ayahku. Seakan kejadian itu sangat dahsyat. Aku mencoba untuk tidak menangis.
“Tapi bukan itu penyebab kematiannya,” kata ayahku. “Ia menggantung dirinya sendiri.”
Aku benar-benar merasa ngeri. Bagaimana orang yang penuh keceriaan dapat melakukan hal seperti itu? Apa ia sedang dihukum? Tapi tak ada alasan untuk melakukannya. Ia memang emosional, bila merasa senang, dunia bagaikan surga, tapi bila sedang marah…yah,kamu tahu bagaimana!
“Oh,” jawabku, tak tahu apa yang harus ku ucapkan.
“Aku minta maaf,”kata ayahku benar-benar minta maaf kepadaku.
Saat seperti ini aku merindukan ibuku. Aku mencintai ayahku, tapi sepertinya ibuku lebih tahu cara menghiburku. Aku berdiri dan memeluk ayah. Ia membalas pelukanku dengan hangat
Beberapa menit kemudian, ibuku datang dengan ceria dan menceritakan pengalaman perjalanannya. Aku dan ayahku tidak banyak berkata-kata hingga menaruh semua barangnya. Kemudian kami menceritakan apa yang terjadi. Ibuku menangis tersedu-sedu. Aku memeluknya dan ikut menangis.
Pagi berikutnya, guruku meminta kami datang bersama orangtua kami masing-masing. Hari itu sekolah hanya berjalan setengah hari sebagai tanda duka cita. Hari itu kami berbagi cerita dan pengalaman kami tentang Ramon. Aku melihat orang-orang yang sebelumnya tak pernah menangis di depanku, sekarang berurai air mata. Hari itu kelasku menampakkan kebersamaan dalam duka.
Beberapa minggu kemudian, kelasku datang ke rumah Ramon untuk membuat taman dalam rangka mengenangnya. Kami menanam cengkeh (pohon kesukaannya) dan bunga-bunga liar. Ibunya memperhatikan kami bekerja penuh air mata, tersentuh dengan apa yang kami lakukan demi mengenang Ramon.
Aku belajar banyak tentang kejadian ini, tapi yang terpenting adalah, selalu bersikap baik pada orang lain. Mungkin tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan atau katakan berdampak buruk bagi orang lain. Dan mungkin tak terlalu berbahahaya jika sasaran kita tepat. Bersikap baik terhadap orang lain dan berpikirlah sebelum bertindak. Kita dapat menyelamatkan nyawa seseorang lewat kebaikan kita.
Aku berharap Ramon menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tempat ia berada sekarang. Kedamaian dan kebahagiaan yang tak ia temukan di dunia ini. Meskipun aku tak dapat mengoper bola ke Ramon lagi, tapi aku selalu mengingat senyumannya.
Dikutip dari: Chiken Soup for the Soul
“Ramon” oleh Emma Fraser, 12 tahun.



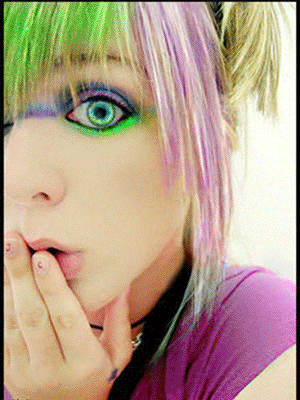
0 komentar:
Posting Komentar